
Text
Membongkar kebisuan menguak tabu : enam kasus kekerasan anak di NAD
Ketika itu Saidi naik ke loteng, Rika mengira itu temannya. Karena sebelumnya juga Rika tak pernah melihat Saidi mendatangi tempat santri perempuan itu.Tiba-tiba Saidi sudah ada di atas dengan berpakaian biasa, mengenakan sarung dan jaket. Sambil berbasa-basi Saidi menanyakan ijazah Rika.Rika ijazahmu di mana?””Ijasah saya di kampung, Ustad,” jawab Rika sambil terus menyeterika. Hanya saja pikirannya tidak tenang. Sesekali ia menoleh ke belakang. ”Kamu kan mau tamat, jadi ijazah itu perlu dibawa ke sini,” kata Saidi. Kali ini ia sudah makin dekat ke Rika yang terus saja menyeterika. Tiba-tiba waktu menoleh ke belakang, rupanya Saidi sudah berjongkok di belakang Rika sambil memegang pinggul Rika. ”Ustad, apa-apaan ini,” tanya Rika. Saidi tidak menjawab, ia justru makin bernafsu sambil memegangi payudara Rika. Alangkah terkejutnya Rika. Ia menepiskan tangan Saidi. ”Ustad, kok kurang ajar begini,” nada Rika mulai meninggi. Ia berlari ke arah jendela sementara Saidi turun ke bawah meninggalkan siswa perempuannya itu begitu saja.
Sepenggal cuplikan dari salah satu kisah tragedi anak manusia di tanah Serambi, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pasca bencana gempabumi dan tsunami 26 Desember dua tahun lalu. Bahwa kekerasan terhadap anak lebih cenderung banyak dilakukan oleh orang-orang yang semestinya menjadi pelindung mereka adalah realita pahit yang harus dihadapi anak-anak. Pencabulan (eksploitasi seksual, termasuk sodomi) yang dilakukan oleh Saidi itu terjadi pada 16 anak didiknya sendiri, baik laki-laki maupun perempuan.
Bahkan kekerasan terhadap anak ternyata terjadi dan dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum yang semena-mena. Sebuah kisah dalam buku ini mengungkap seorang anak sekolah Madrasah Tsanawiyah yang berkonflik dengan hukum karena tertangkap basah mencuri sepeda motor harus mengalami kekerasan ”penyiksaan” sejak tertangkap basa oleh warga yang main hakim sendiri, pemeriksaan oleh kepolisian sampai kekerasan dalam sel penjara yang terdiri dari para kriminal dewasa.
Dan ketika anak itu dianggap sebagai pelaku kejahatan pada umumnya, proses pengadilan seolah-olah sah-sah saja melakukan tindakan kekerasan selama penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum yang justru ”tidak tersentuh” dan ”tidak digugat” dalam proses menuju keadilan itu sendiri. Yang masih terjadi adalah aparat penegak hukum boleh-boleh saja main pukul dan semacamnya terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum,dianggap sebagai ”pesakitan”, apalagi terhadap pelaku kriminal dewasa lainnya.
Toleransi atas tindakan kekerasan nampak dalam kasus pencurian sepeda motor tersebut dengan aksi massa main hakim sendiri, tidak peduli sekalipun pelakunya adalah anak-anak.
Belum tersedia ruang khusus untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum, merupakan wujud ketidak-pedulian negara—lebih tegasnya: pelanggaran HAM---dalam menerapkan hukum positif terhadap kepentingan anak bangsanya sendiri. Dengan demikian, negara telah berkontribusi atas terjadinya kekerasan terhadap anak-anak dalam sel tahanan tersebut. Pelanggaran terhadap UU no.3/1997 tentang Pengadilan Anak dan UU no.23/2002 tentang Perlindungan Anak.
Sistem budaya lokal juga memberikan warna dan pengaruh atas kekerasan yang terjadi pada anak-anak. Feodalisme patriakhi cenderung menempatkan laki-laki sebagai penguasa dan pemimpin yang bisa semena-mena terhadap kaum lemah, seperti perempuan dan anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga---biasanya laki-laki mempunyai kuasa penuh atas rumahtangga dan isinya---dianggap sebagai urusan domestik keluarga masing-masing, oleh karenanya pihak luar tidak boleh mencampurinya. Hal ini berhadapan dengan UU no.23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Kasus menarik terjadi atas pemberlakuan peraturan lokal (Qanun propinsi NAD no.13 tentang maisir/perjudian) terhadap seorang anak perempuan yang dinyatakan bersalah karena terlibat bermain dengan uang yang dianggap maisir, dan karena itu ia juga dihukum—meskipun tidak dicambuk—di depan masjid di hadapan masyarakat umum. Beginikah cara terbaik memperlakukan anak-anak? Sudah dipertimbangkankah dampak dari perlakuan seperti itu bagi perkembangan si-anak? Atau dengan jawaban: lebih baik mengorbankan satu-dua orang anak untuk menyelamatkan ribuan anak lainnya(?)
Ada enam kisah nyata kekerasan terhadap anak dalam buku ini, yang semuanya menarik untuk dipelajari karena mengeksplorasi macam kekerasan terhadap anak yang terjadi dan bagaimana proses penyelesaiannya yang berkaitan langsung dengan tanggungjawab negara melalui aparatnya, juga bagaimana lingkungan sosial menanggapinya. Bahwa ternyata anak masih dianggap sebagai pelaku, juga sebagai korban, sebagaimana cara pandang umumnya terhadap kasus kriminal terjadi pada diri kepolisian dan penegak hukum lainnya, termasuk Wilayatul Hisbah. Dan juga pada masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, perjuangan perubahan bagi kaum perempuan dan anak-anak akan melalui perjalanan panjang perubahan budaya dan sosial.
Buku ini menyajikan tulisan bertutur ala cerpen atau novel yang dilengkapi beberapa ilustrasi, dan pembahasan yang menarik pada bagian epilog untuk mendapatkan garis merah pemaknaan dari semua kisah itu, sehingga tidak membosankan bagi kalangan anak muda.
Daya tarik lainnya dalam buku ini adalah latar belakang budaya masyarakat Aceh yang masih jarang ditemukan di pusat perbukuan. Dan tentunya juga kontras yang kuat antara idealitas dan realitas di Bumi Serambi Mekkah atas enam kisah kekerasan terhadap anak-anak di bumi tersebut.
Buku ini ditujukan untuk advokasi, sekaligus penyadaran publik terhadap kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan dan anak-anak. ”Membongkar Kebisuan, Menguak Tabu” merupakan judul buku sekaligus pernyataan yang berani untuk mengungkap realita kekerasan yang telah, sedang, dan masih terus mengancam kaum perempuan dan anak-anak. Penyajian data-data tentang kekerasan terhadap anak yang tercatat oleh pihak kepolisian, dan media massa merupakan upaya pembelajaran bagi semua pihak untuk lebih terbuka atas masalah ini. Data BAPAS Banda Aceh memperlihatkan 169 anak tercatat sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dan masih status dalam proses. Data Pengadilan Negeri Banda Aceh menunjukkan baru 6 kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan selama tahun 2005. Sedangkan RPK Polda NAD mencatat 14 kasus anak sebagai korban dan 10 kasus anak sebagai pelaku tindak pidana selama tahun 2005-Agustus 2006. Sebagai bahan advokasi dan penyadaran publik, buku ini terwujud melalui proses yang melibatkan banyak pihak, antara lain kelompok pemuda-masyarakat, pihak kepolisian, pemerintah lokal, NGO di Aceh, dan partsipasi dari lembaga PBB seperti unicef.
Catatan kasus itu bukanlah cerminan nyata realitas kekerasan yang terjadi terhadap anak dan kaum perempuan di NAD. Gejala ini merupakan fenomena yang tertangkap mata dan telinga, dan masih banyak lagi yang tak terungkap karena banyak hal yang menghalangi dan memberatka
Availability
| KP.IV.00063 | KP IV.6 MEL m | My Library | Available |
| BK02869PerpusKP | INA VII.39.MEM | My Library | Available |
Detail Information
- Series Title
-
-
- Call Number
-
KP IV.6 MEL m
- Publisher
- Banda Aceh : Yayasan Pusaka Indonesia., 2006
- Collation
-
viii, 147p. :ill. ; 20,5 cm
- Language
-
Indonesia
- ISBN/ISSN
-
979974248X
- Classification
-
KP IV.6
- Content Type
-
-
- Media Type
-
-
- Carrier Type
-
-
- Edition
-
-
- Subject(s)
- Specific Detail Info
-
-
- Statement of Responsibility
-
-
Other version/related
No other version available
File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment
 Computer Science, Information & General Works
Computer Science, Information & General Works  Philosophy & Psychology
Philosophy & Psychology  Religion
Religion  Social Sciences
Social Sciences  Language
Language  Pure Science
Pure Science 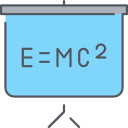 Applied Sciences
Applied Sciences 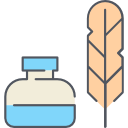 Art & Recreation
Art & Recreation 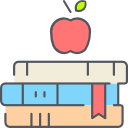 Literature
Literature  History & Geography
History & Geography